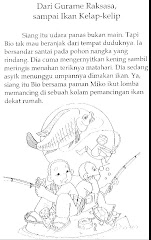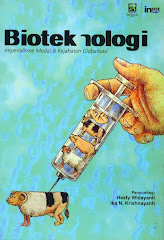Bikin Kompos Sendiri, Lepaskan
Diri dari Ketergantungan
Kicauan suara burung bersautan dengan suara 'rengekan' kambing di belakang
rumah, seakan mengalunkan sebuah lagu dengan iringan hembusan angin lembut.
Udara begitu sejuk siang itu di Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara,
Jawa Tengah. Suasana sekitar rumah yang dipenuhi hijaunya dedaunan tanaman di
halaman muka rumah menambah kesejukan mata yang memandang.
 |
| Bu Bayinah sedang memotong rumput bahan dasar kompos |
Seorang perempuan berkerudung keluar dari rumah dan
menyambut kehadiran kami dengan wajah berseri. Setelah beramah-tamah
sejenak, perempuan yang berprofesi sebagai petani ini menceritakan
pengalamannya dalam mengembangkan pertanian alami (natural farming).
“Saya ini petani PMDN alias Petani Modal Dengkul
dan Nekad,” ungkap Bu Mubayyinah Jauhari, perempuan petani dari Dusun
Pesantren, Merden Wetan, Banjarnegara, Jawa Tengah. “Semula saya berangkat dari
keinginan memperbaiki lahan yang telah rusak, bukan untuk menghasilkan panen
yang tinggi. Saya yakin, kalau lahan yang hancur bisa saya perbaiki, akan menghasilkan
panen yang sehat, dan akhirnya akan mendatangkan keuntungan baik bagi petani
maupun konsumen”.
Bu Bayinah mulai mengembangkan tanaman padi organik seluas setengah hektar.
Untuk mengembangkannya secara alami, dia membutuhkan pupuk kompos yang murni.
Dia pun ingin memaksimalkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya guna mendapatkan
kompos itu. Karena dengan membuat pupuk kompos
sendiri, Bu Bayinah berharap bersama keluarga dan petani lainnya mereka tidak
akan tergantung lagi pada produsen besar. Kini, dari 1 kg benih padi, ia dapat
menghasilkan panen 2 ton (berat basah), dengan rata-rata harga jual berasnya
Rp.8.000/kg.
“Petani bisa bersikap profesional dan mencintai pekerjaannya, melakukannya
sesuai keinginan alam serta bisa memperbaiki lahannya yang telah rusak selama
ini,” jelas Bu Bayinah.
Sesekali Bu Bayinah mendekati dan menyentuh daun tanaman di pekarangan
rumahnya. Dengan selalu
menyunggingkan senyum, ia menceritakan pengalamannya. Menurutnya, bahan-bahan
alami yang ada di sekitar rumahnya sangat bermanfaat, dapat menghasilkan
nutrisi untuk pertumbuhan alami tanaman dan hewan ternaknya.
Dia mencontohkan, air yang ada di dalam pohon pisang bisa menjadi bahan
untuk mendatangkan mikroorganisme lokal melalui proses fermentasi dengan cara menambahkan
gula. Kemudian Bu Bayinah memadupadankan mikroorganisme ini dengan kotoran
ternak untuk menghasilkan kompos yang bisa memperbaiki lahan yang rusak akibat
pemakaian pupuk kimia secara intensif.
Rumput tataria yang tumbuh di
sekitar rumahnya pun bisa bermanfaat sebagai makanan pokok kambing. Tanaman rumpun sejenis padi-padian seberat
1 kilogram ini, jika menjadi pakan kambing maka sekitar 50 persennya dapat
menghasilkan kotoran kambing yang menjadi pupuk kompos. Tanaman orok-orok (Clotalaria) juga banyak menghasilkan nitrogen alami sebagai
pengganti urea, selain bermanfaat pula sebagai pakan kambing.
Di sekitar rumahnya, Bu Bayinah juga memanfaatkan pupuk kompos yang
dihasilkannya sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman selain padi,
seperti singkong dan pohon kelapa. Pohon kelapa yang selama 10 tahun tidak
berbuah dan tumbuh tidak subur, saat ini sudah berbuah sejak tiga bulan lalu.
Tanah di sekitarnya pohon kelapa itu pun menjadi subur dan banyak ditumbuhi tanaman
liar yang bermanfaat sebagai pakan ternak. Tidak hanya itu, air buah kelapa
yang dihasilkan dari pohon kelapa ini juga bermanfaat menghasilkan kalium (salah
satu nutrisi yang dibutuhkan tanaman).
Selain itu, Bu Bayinah juga mendapatkan nutrisi tanaman alami dari
sisa-sisa makanan seperti tulang, ikan, buah, telur, cangkang telur, jahe,
bawang putih, atau empon-empon (jenis-jenis
bumbu dapur). Menurutnya, tulang adalah penghasil nutrisi kalsium, buah nanas menghasilkan
phospor, ikan penghasil protein, jantung pisang untuk peningkatan pertumbuhan
tanaman, bawang putih sebagai antiseptik, tomat sebagai perangsang pertumbuhan
buah, telur keong mas juga perangsang pertumbuhan buah, buah durian sebagai
perangsang pakan kambing, dan asam laktat menghasilkan Laktobacillus atau mikroorganisme pengurai unsur hara tanah agar
bisa diserap tanaman.
Kompos, Manfaat Ganda dari Limbah
Dengan zat perangsang pakan alami, kambing atau domba menjadi mudah makannya.
Selain itu, kotoran kambing jadi tidak berbau, penyakit berkurang dan
kotorannya bisa menjadi kompos yang baik. Urin kambing pun bisa menjadi pupuk
cair organik dan pestisida alami. Bahkan melalui proses fermentasi dengan
menambahkan bawang putih, jahe, temulawak (empon-empon),
urin ternak ini bermanfaat sebagai pupuk dan pestisida alami.
Untuk mendapatkan pupuk kompos dari kotoran kambing, Bu Bayinah menambahkan
30 persen abu sekam, 30 persen gergaji bekas/sisa media tanam jamurnya dan
starter mikroorganisme lokal yang dibuatnya sendiri pula. Kemudian campuran itu
dibiarkan selama 15-21 hari agar terjadi proses fermentasi kotoran kambing.
”Hasilnya, kotoran kambing yang bulat-bulat dan basah itu akan menjadi
kering dan berbentuk serpihan seperti tanah layaknya,” jelas Bu Bayinah. ”Jadi
tidak kalah dengan pupuk buatan pabrik loh!”.
Untuk membuat starter mikroorganisme lokal, Bu Bayinah memanfaatkan rumen ternak
yang dicampur dengan buah nanas, bekatul, terasi, kapur sirih, dan gula merah
yang tidak berasal dari bahan kimia. Dari 1 kilogram starter yang terbentuk, Bu
Bayinah mencampurnya dengan 20 liter air dapat digunakan untuk membasahi
kotoran kambing sebagai bahan kompos. Setelah dibolak-balik selama 15 hari, proses
itu akan menghasilkan kompos yang berkualitas.
Selain menggunakan pupuk kompos, untuk menyuburkan lahan kembali, Bu Bayinah
memanfaatkan tanaman yang sudah tua dan kering. Tanaman itu dipangkas dan
dikubur dalam lahan itu sebagai berkah untuk lahan.
Buktikan dengan Keberhasilan
Dengan mengembangkan pertanian alami ini, lahan Bu Bayinah menjadi subur
kembali. Dia juga mengaku lebih sedikit menggunakan benih tanaman. Sebelumnya
dia bisa menghabiskan 80 kilogram benih, tapi setelah menggunakan nutrisi
tanaman alami, benih yang digunakannya hanya 5 kilogram. Jenis padi yang
ditanamnya adalah sintanur dan jasmin.
Meski masih berproduksi dalam skala kecil, namun perempuan yang juga membudidayakan
tanaman bunga rosela dan jamur ini mengaku bisa menghasilkan berasnya lebih banyak
ketimbang sebelum mengembangkan pertanian alami. Bahkan dia bisa memasarkannya
ke luar kota seperti Purwokerto sebanyak 1-2 kuintal dan Semarang 5 kuintal.
Bu Bayinah juga mendapatkan penghasilan dari budidaya jamur dan rosela. ”Hasilnya
lumayan untuk menghidupi diri sendiri dan karyawan,” jelasnya.
Semula petani tetangganya tidak yakin dengan apa yang dilakukan Bu Bayinah
dengan pertanian alami. Namun akhirnya dengan ketekunan dan keberhasilan yang
dicapai Bu Bayinah, masyarakat petani lainnya jadi banyak yang tertarik. Banyak
di antara mereka yang ingin mengembangkan pertanian alami. Saat ini sudah ada
dua kelompok petani yang mengembangkan pertanian alami di wilayahnya, yaitu
kelompok Sidodadi dan Sidomakmur.
”Saya juga mengajak ibu-ibu di forum pengajian untuk beralih ke pertanian
alami atau organik. Meski selama ini banyak dari mereka yang tidak ikut turun
ke sawah,” ungkap lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga,
Jakarta ini.
Saat ini sudah banyak perempuan di sekitar rumah Bu Bayinah yang ikut turun
ke sawah. Dengan membawa daun bambu, mereka ingin memanfaatkannya untuk
menyerap residu bahan-bahan kimia dari sawah. ”Dengan daun-daun bambu, konsentrasi
residu berkurang dan lahan dapat segera pulih,” ujar Bu Bayinah (dipubliksikan dalam Buletin Bina Desa 2009/disarikan dari wawancara dengan Bu
Bayinah/ani purwati/ink).