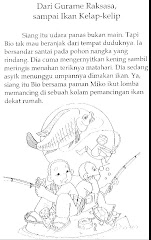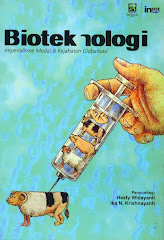Perdagangan yang Adil untuk Ketahanan Pangan Semua
Ketika manusia masih sedikit jumlahnya, mereka yang punya bahan pangan akan menukarkan sebagian miliknya dengan milik orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Pangan memang berharga untuk dipertukarkan saat itu. Kini, dari berbagai pelosok bumi manusia menghasilkan pangan. Namun sesungguhnya lebih banyak manusia yang tidak kebagian pangan, entah karena tidak dapat mengakses pangan itu, seperti orang miskin, atau karena keterbatasan sumber daya yang dapat diolah menjadi pangan seperti di daerah kering, atau petani tak punya tanah untuk diolah. Namun tidak sedikit orang yang terbatas aksesnya kepada sumber daya pangan akibat tidak layak dikonsumsinya pangan tersebut.
Mengingat memperoleh pangan yang layak, aman, dan terjangkau merupakan hak asasi manusia, maka dengan kenyataan di atas banyak manusia menjadi korban pelanggaran hak atas pangan ini, seperti muncul pada kasus-kasus rawan pangan, busung lapar, kurang gizi, hingga kematian.
Masih sedikit orang yang menyadari bahwa harga produk pertanian yang murah menyumbang pada pelanggaran hak atas pangan bagi petani sebagai produsen. Karena harga komoditas pertanian yang layak bagi petani (produsen sekaligus konsumen) juga merupakan hak asasi yang melekat pada petani. Oleh karena itu, mendapatkan akses pasar dan harga yang pantas atas komoditas yang dihasilkan, merupakan prasyarat agar petani dapat menyejahterakan diri dan keluarganya. Hal itu dapat terwujud dalam sistem perdagangan produk pertanian yang berkeadilan. Bukannya konsep Perjanjian Pertanian (Agreement on Agriculture/AoA) yang ditawarkan World Trade Organization (WTO) yang lebih berpihak kepada negara maju dan pemilik modal.
Dengan konsep-konsep yang diusung WTO, komoditas petani dari negara berkembang tidak akan mendapat perlindungan. Dan mudah dijatuhkan oleh produk dari negara maju yang sektor pertaniannya dibantu penuh oleh pemerintahnya. Produk-produk itulah yang kini membanjiri negara berkembang. Tak mengherankan, protes negara berkembang (terutama negara yang tergabung dalam kelompok G 33) menjadi batu sandungan dalam perundingan-perundingan pertanian di WTO.
Sementara itu, pemerintah sibuk mengeluarkan kebijakan konversi lahan dengan berbagai dalih. Konversi lahan ini bukan semata untuk kepentingan pertanian, namun terkait dengan paradigma (cara pandang) pertanahan yang dianut penguasa. Maka lahan petani berpindah tangan dan berganti fungsi menjadi mesin-mesin penghasil uang. Contohnya lahan penghasil pangan menjelma menjadi kebun-kebun sawit, coklat, atau menjadi kawasan wisata yang lebih cepat menghasilkan uang bagi pemilik modal. Tidak sedikit pula petani yang menjadi tuna kisma (tak punya tanah) atau menjadi buruh di lahannya sendiri.
Di sisi lain, petani terus dipaksa mensubsidi masyarakat perkotaan untuk memenuhi kebutuhan pangannya, sementara harga produk pertanian itu sendiri dihargai sangat murah sehingga petani tetap tidak sejahtera. Seperti beras lokal petani kita, selain murah juga dihajar beras impor.
Rancangan Undang-undang Lahan Abadi yang sedang dibahas pun memihak para pemilik modal, bahkan melegalkan kepemilikan lahan oleh perusahaan. RUU ini akan menjadi pintu masuk modal semata, penguatan kepemilikan lahan di tangan segelintir orang, penyeragaman pangan karena sangat bias padi (sawah), dan petani hanya menjadi sapi perah yang terus menderita.
Perdagangan pertanian yang adil sudah selayaknya dirasakan petani dan kita.
Kamis, 25 September 2008
Pelestari Lingkungan
Mereka Penjaga Lingkungan
Pada bulan April, Mei, dan Juni ada tiga hari yang diperingati orang sedunia, yaitu Hari Bumi (22 April), Hari Buruh atau May Day (1 Mei), dan Hari Lingkungan Hidup (5 Juni). Apa pun yang melatarbelakangi ditetapkannya ketiga hari itu untuk diperingati, masih sedikit orang yang menyadari makna di balik ketiganya.
Perjuangan kelas buruh untuk mencapai kesejahteraan hampir selalu menemui batu sandungan, karena hampir semua pihak berpaling kepada modal. Pengusaha, pemilik tanah, “wakil rakyat”, bahkan peraturan perundangan pun (termasuk para pembuatnya) memalingkan wajah mereka kepada uang. Buruh semakin terpinggirkan dan tak memiliki kepastian masa depan. Lihatlah kasus lumpur Lapindo, tampak jelas siapa saja yang sudah berani membuka topeng dan berpaling ke modal.
Sementara manusia saling bertikai, banyak orang berkata, bumi semakin tua makin berkurang kemampuannya untuk menopang kehidupan miliaran manusia dan makhluk hidup lainnya beserta aktivitas mereka. Stephen Hawking, fisikawan terkemuka dunia seperti dikutip Kompas (2/5/2007) mengatakan, “Kehidupan di bumi semakin berada dalam risiko untuk disapu oleh bencana, seperti pemanasan global mendadak, perang nuklir, virus hasil rekayasa genetika, dan bahaya lain”.
Namun lingkungan rusak, banjir, tanah longsor, gelombang panas, perubahan iklim, dan berbagai malapetaka lain tampaknya bukan karena semata bumi yang semakin renta. Tetapi tangan-tangan manusia yang semakin rajin menjamah dan memperlakukan sumber daya yang bukan miliknya secara sewenang-wenang telah berperan besar dalam merusak alam. Di negara maju, ramai-ramai pemilik modal membolongi lapisan ozon dengan gas-gas buangan industri mereka sehingga gas-gas berbahaya masuk ke bumi tanpa terhalang. Sementara di negara berkembang, seperti Indonesia, setiap hari orang menggunduli hutan dengan kecepatan 10 x lapangan sepak bola per menit. Bahaya lingkungan dan kesehatan juga telah lama menyusup ke pertanian kita.
Demi meraup keuntungan berlipat ganda, perusahaan-perusahaan multinasional penghasil benih dan pestisida, bersekongkol dengan penyelenggara negara dan memaksa petani membeli benih dan asupan pertanian hasil rekayasa genetik. Kini, kelapa sawit, kopi, vanili, tebu, dan cokelat transgenik bergantian menyerbu kebun-kebun di negara berkembang, menyusul jagung dan kapas hasil rekayasa genetik yang telah lebih dulu merusak kehidupan petani kecil. Sementara itu, “pupuk organik” yang terbuat dari tepung tulang sapi gila pun meluncur deras ke negeri-negeri yang peraturannya amburadul.
Perebutan penguasaan sumber-sumber agraria lainnya juga berlangsung di Bumi Nusantara. Penguasa, penyelenggara negara, pemilik modal raksasa, dan kekuatan militer dengan paksa berusaha menguasai sumber-sumber agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran segelintir orang berkuasa. Tak segan-segan mereka merampasnya dari tangan rakyat miskin yang hanya berharap dapat hidup dari sejengkal tanah. Begitu juga sumber air bersih yang makin sulit didapat rakyat, masih juga menjadi incaran industri-industri air mancanegara yang memanfaatkan kaki-tangan mereka di berbagai daerah.
Bagi pemilik modal, bumi, lingkungan, bahkan manusia dan makhluk hidup seisi alam ini hanyalah komoditas yang dapat dibongkar-pasang lalu dimainkan harganya di pasar saham. Namun bagi petani, nelayan, buruh, dan rakyat kecil lainnya, sejengkal tanah, setetes air, segenggam benih yang mereka miliki adalah benteng pertahanan dalam hidup ini. Merekalah penjaga alam, pelestari lingkungan di garis terdepan. Pernahkah kita menyadarinya?
Pada bulan April, Mei, dan Juni ada tiga hari yang diperingati orang sedunia, yaitu Hari Bumi (22 April), Hari Buruh atau May Day (1 Mei), dan Hari Lingkungan Hidup (5 Juni). Apa pun yang melatarbelakangi ditetapkannya ketiga hari itu untuk diperingati, masih sedikit orang yang menyadari makna di balik ketiganya.
Perjuangan kelas buruh untuk mencapai kesejahteraan hampir selalu menemui batu sandungan, karena hampir semua pihak berpaling kepada modal. Pengusaha, pemilik tanah, “wakil rakyat”, bahkan peraturan perundangan pun (termasuk para pembuatnya) memalingkan wajah mereka kepada uang. Buruh semakin terpinggirkan dan tak memiliki kepastian masa depan. Lihatlah kasus lumpur Lapindo, tampak jelas siapa saja yang sudah berani membuka topeng dan berpaling ke modal.
Sementara manusia saling bertikai, banyak orang berkata, bumi semakin tua makin berkurang kemampuannya untuk menopang kehidupan miliaran manusia dan makhluk hidup lainnya beserta aktivitas mereka. Stephen Hawking, fisikawan terkemuka dunia seperti dikutip Kompas (2/5/2007) mengatakan, “Kehidupan di bumi semakin berada dalam risiko untuk disapu oleh bencana, seperti pemanasan global mendadak, perang nuklir, virus hasil rekayasa genetika, dan bahaya lain”.
Namun lingkungan rusak, banjir, tanah longsor, gelombang panas, perubahan iklim, dan berbagai malapetaka lain tampaknya bukan karena semata bumi yang semakin renta. Tetapi tangan-tangan manusia yang semakin rajin menjamah dan memperlakukan sumber daya yang bukan miliknya secara sewenang-wenang telah berperan besar dalam merusak alam. Di negara maju, ramai-ramai pemilik modal membolongi lapisan ozon dengan gas-gas buangan industri mereka sehingga gas-gas berbahaya masuk ke bumi tanpa terhalang. Sementara di negara berkembang, seperti Indonesia, setiap hari orang menggunduli hutan dengan kecepatan 10 x lapangan sepak bola per menit. Bahaya lingkungan dan kesehatan juga telah lama menyusup ke pertanian kita.
Demi meraup keuntungan berlipat ganda, perusahaan-perusahaan multinasional penghasil benih dan pestisida, bersekongkol dengan penyelenggara negara dan memaksa petani membeli benih dan asupan pertanian hasil rekayasa genetik. Kini, kelapa sawit, kopi, vanili, tebu, dan cokelat transgenik bergantian menyerbu kebun-kebun di negara berkembang, menyusul jagung dan kapas hasil rekayasa genetik yang telah lebih dulu merusak kehidupan petani kecil. Sementara itu, “pupuk organik” yang terbuat dari tepung tulang sapi gila pun meluncur deras ke negeri-negeri yang peraturannya amburadul.
Perebutan penguasaan sumber-sumber agraria lainnya juga berlangsung di Bumi Nusantara. Penguasa, penyelenggara negara, pemilik modal raksasa, dan kekuatan militer dengan paksa berusaha menguasai sumber-sumber agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran segelintir orang berkuasa. Tak segan-segan mereka merampasnya dari tangan rakyat miskin yang hanya berharap dapat hidup dari sejengkal tanah. Begitu juga sumber air bersih yang makin sulit didapat rakyat, masih juga menjadi incaran industri-industri air mancanegara yang memanfaatkan kaki-tangan mereka di berbagai daerah.
Bagi pemilik modal, bumi, lingkungan, bahkan manusia dan makhluk hidup seisi alam ini hanyalah komoditas yang dapat dibongkar-pasang lalu dimainkan harganya di pasar saham. Namun bagi petani, nelayan, buruh, dan rakyat kecil lainnya, sejengkal tanah, setetes air, segenggam benih yang mereka miliki adalah benteng pertahanan dalam hidup ini. Merekalah penjaga alam, pelestari lingkungan di garis terdepan. Pernahkah kita menyadarinya?
Pangan
Pangan dan Martabat Manusia
Dunia kini merupakan rumah bagi 850 juta manusia yang kelaparan dan menderita gizi buruk. Kelangkaan pangan, rendahnya kualitas pangan, tercemarnya air minum, dan kemunculan berbagai penyakit, mulai menjadi pemandangan yang biasa kita temukan di sekitar kita, bahkan menjadi bagian dari kehidupan perempuan, laki-laki, dan anak-anak di seluruh dunia. Apakah planet bumi tidak lagi sanggup memberi makan penduduknya?
Bukan kurangnya pr oduksi pangan yang menjadi penyebab keadaan ini. Tiadanya akses terhadap pangan bagi rakyat marjinal dan berkekurangan inilah yang menyebabkan ratusan juta manusia di dunia kelaparan dan kurang gizi. Dengan kalimat lain, keterbatasan penguasaan atas sumber daya dasar, seperti tanah dan benih atau penghasilan untuk memperoleh pangan yang menopang kehidupan inilah yang menjadi penyumbang penurunan martabat manusia.
oduksi pangan yang menjadi penyebab keadaan ini. Tiadanya akses terhadap pangan bagi rakyat marjinal dan berkekurangan inilah yang menyebabkan ratusan juta manusia di dunia kelaparan dan kurang gizi. Dengan kalimat lain, keterbatasan penguasaan atas sumber daya dasar, seperti tanah dan benih atau penghasilan untuk memperoleh pangan yang menopang kehidupan inilah yang menjadi penyumbang penurunan martabat manusia.
Data yang dikeluarkan oleh FIAN Internasional, menunjukkan ¾ dari orang kelaparan di dunia tinggal di pedesaan, tempat selayaknya pangan dihasilkan; perempuan, masyarakat adat, anak balita, serta korban bencana alam dan perang adalah kelompok yang paling parah terkena dampak kelaparan dan gizi buruk; hampir 1 dari 7 orang di dunia tidak mendapatkan pangan yang cukup untuk tetap sehat dan menjalani hidup yang aktif; setiap tahun lebih dari 5,5 juta anak meninggal akibat penyakit yang berhubungan dengan gizi buruk; setiap menit 24 orang mati kelaparan; bahkan setiap 5 detik 1 orang anak kecil mati kelaparan. Jadi, begitu Anda selesai membaca tulisan ini selama 30 detik, sedikitnya ada 6 manusia di dunia yang harus kehilangan nyawa karena lapar atau gizi buruk.
Mendapat pangan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi (menyetujui) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ekosob) melalui Undang-undang No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights di mana negara berkewajiban memenuhi dan melindungi hak atas pangan rakyat.
Namun petani dan rakyat pedesaan justru menjadi kelompok yang paling rentan kelaparan, belum lagi nelayan kecil yang tersingkir dari lautnya sendiri karena keberadaan kapal-kapal pukat milik pengusaha, dan k aum miskin kota yang memang tidak punya akses ke sumber daya dan penghasilan yang layak. Mereka tidak pernah diuntungkan dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah sebagai pemegang amanat atas terpenuhinya hak atas pangan setiap rakyatnya.
aum miskin kota yang memang tidak punya akses ke sumber daya dan penghasilan yang layak. Mereka tidak pernah diuntungkan dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah sebagai pemegang amanat atas terpenuhinya hak atas pangan setiap rakyatnya.
Meski KTT Pangan Sedunia 2006 mengakui angka kelaparan dunia tidak semakin menurun, namun justru terus meningkat, neoliberalisme dan neoimperialisme (penjajahan baru) melalui perusahaan-perusahaan multinasional, lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia, dan lain-lain), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian bilateral dan regional semakin dalam menancapkan cengkeramannya atas negara berkembang. Pemerintah pun melepaskan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar rakyatnya kepada kekuatan modal. Tak mengherankan, harga-harga kebutuhan pokok semakin tinggi, dan pengalihan lahan-lahan pangan produktif menjadi lahan tanaman ekspor semakin marak, sementara rakyat miskin bertumbangan ke bumi.
Memberdayakan rakyat untuk dapat mendokumentasi pelanggaran hak atas pangan, mengorganisasi diri sehingga melahirkan kekuatan untuk mendesak pemerintah, serta membangun aliansi dan dukungan internasional menjadi agenda penting yang harus segera kita laksanakan agar hak-hak rakyat atas pangan kembali terpenuhi.
Dunia kini merupakan rumah bagi 850 juta manusia yang kelaparan dan menderita gizi buruk. Kelangkaan pangan, rendahnya kualitas pangan, tercemarnya air minum, dan kemunculan berbagai penyakit, mulai menjadi pemandangan yang biasa kita temukan di sekitar kita, bahkan menjadi bagian dari kehidupan perempuan, laki-laki, dan anak-anak di seluruh dunia. Apakah planet bumi tidak lagi sanggup memberi makan penduduknya?
Bukan kurangnya pr
 oduksi pangan yang menjadi penyebab keadaan ini. Tiadanya akses terhadap pangan bagi rakyat marjinal dan berkekurangan inilah yang menyebabkan ratusan juta manusia di dunia kelaparan dan kurang gizi. Dengan kalimat lain, keterbatasan penguasaan atas sumber daya dasar, seperti tanah dan benih atau penghasilan untuk memperoleh pangan yang menopang kehidupan inilah yang menjadi penyumbang penurunan martabat manusia.
oduksi pangan yang menjadi penyebab keadaan ini. Tiadanya akses terhadap pangan bagi rakyat marjinal dan berkekurangan inilah yang menyebabkan ratusan juta manusia di dunia kelaparan dan kurang gizi. Dengan kalimat lain, keterbatasan penguasaan atas sumber daya dasar, seperti tanah dan benih atau penghasilan untuk memperoleh pangan yang menopang kehidupan inilah yang menjadi penyumbang penurunan martabat manusia.Data yang dikeluarkan oleh FIAN Internasional, menunjukkan ¾ dari orang kelaparan di dunia tinggal di pedesaan, tempat selayaknya pangan dihasilkan; perempuan, masyarakat adat, anak balita, serta korban bencana alam dan perang adalah kelompok yang paling parah terkena dampak kelaparan dan gizi buruk; hampir 1 dari 7 orang di dunia tidak mendapatkan pangan yang cukup untuk tetap sehat dan menjalani hidup yang aktif; setiap tahun lebih dari 5,5 juta anak meninggal akibat penyakit yang berhubungan dengan gizi buruk; setiap menit 24 orang mati kelaparan; bahkan setiap 5 detik 1 orang anak kecil mati kelaparan. Jadi, begitu Anda selesai membaca tulisan ini selama 30 detik, sedikitnya ada 6 manusia di dunia yang harus kehilangan nyawa karena lapar atau gizi buruk.
Mendapat pangan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi (menyetujui) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ekosob) melalui Undang-undang No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights di mana negara berkewajiban memenuhi dan melindungi hak atas pangan rakyat.
Namun petani dan rakyat pedesaan justru menjadi kelompok yang paling rentan kelaparan, belum lagi nelayan kecil yang tersingkir dari lautnya sendiri karena keberadaan kapal-kapal pukat milik pengusaha, dan k
 aum miskin kota yang memang tidak punya akses ke sumber daya dan penghasilan yang layak. Mereka tidak pernah diuntungkan dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah sebagai pemegang amanat atas terpenuhinya hak atas pangan setiap rakyatnya.
aum miskin kota yang memang tidak punya akses ke sumber daya dan penghasilan yang layak. Mereka tidak pernah diuntungkan dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah sebagai pemegang amanat atas terpenuhinya hak atas pangan setiap rakyatnya.Meski KTT Pangan Sedunia 2006 mengakui angka kelaparan dunia tidak semakin menurun, namun justru terus meningkat, neoliberalisme dan neoimperialisme (penjajahan baru) melalui perusahaan-perusahaan multinasional, lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia, dan lain-lain), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian bilateral dan regional semakin dalam menancapkan cengkeramannya atas negara berkembang. Pemerintah pun melepaskan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar rakyatnya kepada kekuatan modal. Tak mengherankan, harga-harga kebutuhan pokok semakin tinggi, dan pengalihan lahan-lahan pangan produktif menjadi lahan tanaman ekspor semakin marak, sementara rakyat miskin bertumbangan ke bumi.
Memberdayakan rakyat untuk dapat mendokumentasi pelanggaran hak atas pangan, mengorganisasi diri sehingga melahirkan kekuatan untuk mendesak pemerintah, serta membangun aliansi dan dukungan internasional menjadi agenda penting yang harus segera kita laksanakan agar hak-hak rakyat atas pangan kembali terpenuhi.
Langganan:
Komentar (Atom)