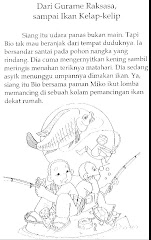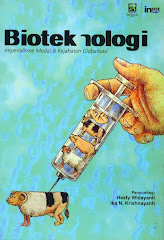Krisis Pangan Buntut Peminggiran Petani dan Pertanian
Dalam suatu kuliah umum di sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta, seorang pengajar menayangkan presentasinya pada sebuah layar putih. Tayangan itu berisi pernyataan berikut: “Petani, riwayatmu kini: ditinggi-tinggikan dalam harapan mulia pembuat undang-undang, dibatas-batasi dalam ketentuan undang-undang, dicurang-curangi oleh perusahaan besar, bisa-bisa disuruh tanam paksa oleh pemerintah”.
Terdengar akrab di telinga? Butir-butir pernyataan di atas, memang jelas terlihat dalam dunia pertanian dan kehidupan petani kita saat ini. Tidak sedikit perundang-undangan telah lahir untuk mengatur sektor yang menjadi sumber kehidupan sebagian besar penduduk negeri agraris ini, malah menjadi malapetaka bagi petani.
Dari total lahan Indonesia seluas 181,1 juta hektar, sekitar seperempatnya atau 44,8 juta hektar merupakan lahan pertanian. Sektor pertanian Indonesia memberi sumbangsih kepada 15,2% total GDP pada tahun 2004, menyediakan lapangan kerja bagi 43,8% penduduk Indonesia pada tahun 2001, memberikan 11,37% penerimaan ekspor, serta menghasilkan 12,10% total pembayaran impor (Presentasi hasil penelitian Asian Farmers Association/AFA, November 2008).
Selama berjalannya peradaban manusia, pertanian memang memanfaatkan, membudidayakan, dan memelihara sumber daya yang tersedia beserta ekosistemnya. Pertanian juga menopang perekonomian dan budaya yang hidup di wilayah pedesaan, serta menyimpan pengetahuan dan kearifan tentang berbagai praktik pertanian yang sangat beragam. Namun ketika kebijakan-kebijakan perdagangan dirumuskan, tidak ada satupun pemikiran yang mempertimbangkan peran pertanian yang sangat multifungsional ini. Contohnya, kebijakan liberaslisasi perdagangan dunia melalui AoA (Agreement on Agriculture) dalam World Trade Organization (WTO) menjadikan beras hanya sebagai komoditas di pasar dunia sehingga mendorong terjadinya spekulasi harga dan investasi untuk beras. Pertanian hanya dipandang dari perspektif ekonomi saja. Demi memaksimalkan nilai produksi, kebijakan perdagangan internasional mendorong produksi pertanian masuk ke dalam persaingan internasional yang sangat ketat dan mengakibatkan terancamnya peran pertanian yang sangat multifungsi ini (Heinrich Boll Stiftung, Misereor, & Wuppertal Institute, Slow Trade – Sound Farming, 2008: 6).
Minggir, Tanaman Pangan!
Krisis Pangan pun MelandaDalam suatu kuliah umum di sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta, seorang pengajar menayangkan presentasinya pada sebuah layar putih. Tayangan itu berisi pernyataan berikut: “Petani, riwayatmu kini: ditinggi-tinggikan dalam harapan mulia pembuat undang-undang, dibatas-batasi dalam ketentuan undang-undang, dicurang-curangi oleh perusahaan besar, bisa-bisa disuruh tanam paksa oleh pemerintah”.
Terdengar akrab di telinga? Butir-butir pernyataan di atas, memang jelas terlihat dalam dunia pertanian dan kehidupan petani kita saat ini. Tidak sedikit perundang-undangan telah lahir untuk mengatur sektor yang menjadi sumber kehidupan sebagian besar penduduk negeri agraris ini, malah menjadi malapetaka bagi petani.
Dari total lahan Indonesia seluas 181,1 juta hektar, sekitar seperempatnya atau 44,8 juta hektar merupakan lahan pertanian. Sektor pertanian Indonesia memberi sumbangsih kepada 15,2% total GDP pada tahun 2004, menyediakan lapangan kerja bagi 43,8% penduduk Indonesia pada tahun 2001, memberikan 11,37% penerimaan ekspor, serta menghasilkan 12,10% total pembayaran impor (Presentasi hasil penelitian Asian Farmers Association/AFA, November 2008).
Selama berjalannya peradaban manusia, pertanian memang memanfaatkan, membudidayakan, dan memelihara sumber daya yang tersedia beserta ekosistemnya. Pertanian juga menopang perekonomian dan budaya yang hidup di wilayah pedesaan, serta menyimpan pengetahuan dan kearifan tentang berbagai praktik pertanian yang sangat beragam. Namun ketika kebijakan-kebijakan perdagangan dirumuskan, tidak ada satupun pemikiran yang mempertimbangkan peran pertanian yang sangat multifungsional ini. Contohnya, kebijakan liberaslisasi perdagangan dunia melalui AoA (Agreement on Agriculture) dalam World Trade Organization (WTO) menjadikan beras hanya sebagai komoditas di pasar dunia sehingga mendorong terjadinya spekulasi harga dan investasi untuk beras. Pertanian hanya dipandang dari perspektif ekonomi saja. Demi memaksimalkan nilai produksi, kebijakan perdagangan internasional mendorong produksi pertanian masuk ke dalam persaingan internasional yang sangat ketat dan mengakibatkan terancamnya peran pertanian yang sangat multifungsi ini (Heinrich Boll Stiftung, Misereor, & Wuppertal Institute, Slow Trade – Sound Farming, 2008: 6).
Minggir, Tanaman Pangan!
Kenaikan harga-harga di sepanjang tahun 2008 tak hanya melanda bahan pangan pokok dan komoditas dasar lainnya, tapi juga bahan bakar minyak. Pemangkasan subsidi BBM menimbulkan keresahan dan kesengsaraan rakyat kecil, sementara kenaikan bahan pangan sudah lebih dulu menimbulkan dampak mengerikan, mulai dari korban busung lapar, kurang gizi, tewas kelaparan, atau bunuh diri. Krisis pangan merebak ke mana-mana, bahkan sampai ke beberapa negara maju.
Namun, sementara di negara-negara berkembang stok bahan pangan pokok seperti beras, gula, terigu, minyak goreng, kedelai dan lain-lain berada di ambang kelangkaan atau melesat naik harganya hingga tak terbeli oleh masyarakat, di negara maju (terutama di Eropa dan Amerika Serikat) permintaan atau penggunaan bahan bakar hayati dari produk pertanian (agrofuel atau biofuel), seperti minyak sawit, kedelai, jagung, singkong, jarak, tebu, dan lain-lain justru semakin meningkat.
Dengan dalih mengatasi perubahan iklim, negara-negara maju mengkampanyekan penggunaan energi nabati yang tampaknya ramah lingkungan. Lalu mengerahkan modalnya, mengekspansi lahan pertanian pangan di negara berkembang, menyulapnya menjadi lahan penghasil agrofuel atau biofuel. Tak mengherankan jika di Indonesia, kini tak kurang dari 120.000 hektar per tahun lahan pertanian beralih fungsi menjadi lokasi industri, perumahan, dan sektor non pangan lainnya, sementara eksploitasi besar-besaran atas tanah dan air terus berlangsung.
Penyelenggara negara tentu melakukan segala upaya demi mendapatkan devisa dari sumber energi alternatif ini, yang notabene “melayani” kebutuhan energi negara maju. Contohnya, kesepakatan Jepang-Indonesia yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2008, menyebutkan Indonesia diharuskan memasok 80% kebutuhan energi Jepang. Bahkan Menteri Pertanian dan Menteri Sumber Daya Energi Indonesia pernah mengumumkan tekadnya bahwa Indonesia harus menjadi negara nomor satu penghasil agrofuel (Presentasi Direktur Bina Desa, Dwi Astuti pada Refleksi Pengorganisasian Bina Desa, Juli 2008).
Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional telah mencanangkan digunakannya energi alternatif. Dalam Perpres itu, dicantumkan bahwa pada tahun 2005 penggunaan biofuel mencapai 10 persen dari kebutuhan bahan bakar dalam negeri. Pemerintah bahkan menargetkan produksi biodiesel pada tahun 2010 mencapai 900.000 kiloliter.
Segera saja, pintu bagi pemodal asing yang bermitra dengan industri/pemerintah setempat terbuka seluas-luasnya untuk membentangkan kebun sawit, jagung, singkong, dan sebagainya guna menghasilkan bahan bakar nabati. PT Sakheta Minahasa Selatan (hasil patungan dengan PT Sakheta Indonesia Pratama) akan membangun pabrik biodiesel berkapasitas 1,5 juta liter biodiesel per tahun. Di Kabupaten Minahasa Selatan sudah ada penanaman jarak di areal seluas 10 ribu hektar, dan di Tombatu (Minahasa Tenggara) seluas 600 hektar. Selanjutnya pemda akan terus melakukan perluasan area tanaman jarak, sehingga kapasitas produksi pabrik biodiesel berkapasitas 1,5 juta liter setiap tahun itu dapat terpenuhi. Hasilnya akan diekspor ke China.
Pengembangan tanaman jarak pagar (Jatropha curcas) sebagai bahan baku bioenergi, bahan bakar alternatif yang disebut-sebut “ramah lingkungan” terus dilakukan, termasuk di Jawa Tengah. Areal penanaman di provinsi ini ditargetkan sekitar 32 ribu hektar melalui model perkebunan sosial berupa kerja sama antara Perhutani, PMA, dan masyarakat sekitar hutan. Perhutani menyediakan lahan tumpang sari, sementara pihak PMA menyediakan modal kerja, bibit hingga pembelian hasil petani. Penanaman jarak pagar di Jateng tersebar di 20 KPH Perhutani. Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, pihak PMA bahkan membangun pabrik pengolah minyak jarak untuk menjawab kekhawatiran persolan pemasaran (http://www.tvri.co.id/).
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie ketika meninjau tanaman jarak di Desa Tondegesen, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) September lalu meminta petani agar menanam tanaman jarak sebanyak-banyaknya. Menurutnya, sampai saat ini tanaman jarak yang berhasil dikembangkan oleh petani di Indonesia baru sedikit sekali, padahal pemerintah ingin agar jumlah ditanam sebanyak yang mampu dibudidaya petani. Penanaman tanaman jarak di Indonesia saat ini baru berkisar 10 ribu hektar yang tersebar di Lampung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulut.
Menurut Bupati Minahasa, rencana penanaman jarak mencapai luas areal 11 ribu hektar, terpusat di empat kecamatan, dan diharapkan tercapai dalam dua tahun mendatang. Di Desa Tondegesan, Kecamatan Tompaso, dari target 25 hektar dengan jumlah bibit jarak berkisar 400 ribu, baru ditanami sekitar dua hektar, diharapkan luas areal keseluruhan tersebut dapat ditanami sampai tahun depan. Di kecamatan lain, saat ini masih terus digenjot oleh pemerintah daerah.
Namun lokasi yang ditanami jarak di Tondegesan, ternyata diapit oleh lahan yang ditanami jagung yang sudah meninggi. Sebelum ditanami jarak, petani setempat bisa mendapatkan penghasilan sebanyak 1 ton dari setiap hektar lahan jagung. Kini, sudah ada investor yang akan mengelola hasil tanaman jarak dari areal seluas 25 hektar di desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan, dan akan diikuti oleh sejumlah kecamatan lainnya. Manusia pun harus memperebutkan sumber daya lahan dan pangan dari kepentingan mesin-mesin berbahan bakar biofuel ini.
Mesin versus Manusia
Perubahan konsumsi dari energi berbasis fosil, seperti BBM, ke energi alternatif berbasis bahan hayati yang terbarukan tampak sebagai langkah ekologis (ramah lingkungan) dan berkelanjutan. Namun, pengalihan lahan-lahan tanaman pangan menjadi lahan penghasil biofuel menjadi malapetaka lainnya bagi para petani, bahkan manusia secara umum. Dapat kita bayangkan jika jutaan ton jagung, gandum, kacang-kacangan, kedelai, dan minyak kelapa sawit menjadi biofuel, sebuah pengabaian bagi penduduk yang kelaparan. Krisis pangan dan kerusakan lingkungan bukannya teratasi, tetapi semakin memburuk. Misalnya, untuk menghasilkan 13 galon etanol, diperlukan 232 kg jagung (yang dapat dikonsumsi seorang anak di Zambia atau Meksiko selama satu tahun).
Rakyat hanya kebagian lingkungan yang rusak, sementara mereka tetap kelaparan akibat krisis pangan, karena harus bersaing dengan mesin-mesin pabrik dan kendaraan di negara maju. Inilah yang disebut Jean Ziegler (pakar dari PBB) sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Karena dengan alasan pengalihan beberapa bentuk produk pangan maupun areal pertanian pangan untuk menghasilkan biofuel secara langsung menyebabkan kelangkaan pangan dan kelaparan bagi kaum miskin di berbagai belahan dunia (Oroh, F.S.J, Biofuel: Antara Peluang Bisnis dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Manado Post, 26 Juni 2008).
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memaparkan beberapa faktor penyebab krisis, mulai dari meningkatnya permintaan global dan berkurangnya produksi pangan akibat perubahan iklim secara ekstrem sampai kenaikan harga minyak. Harga pangan pun goncang. Penggunaan agrofuel secara besar-besaran dan spekulasi pasar uang disebut-sebut pula menjadi penyebab naiknya harga pangan. Bahkan Bank Dunia mengakui, agrofuel berperan dalam krisis pangan dengan kenaikan harga pangan secara berarti. Ini ditandai dengan naiknya permintaan bahan mentah untuk menjalankan mesin atau pabrik, dan akhirnya bersaing dengan tanaman pangan. Seluruh harga pangan pun melesat naik (Imam Suharto & Dwi Astuti, “Krisis Pangan Jawaban atas Pengabaian terhadap Petani”, 2008).
Apa yang dapat kita lakukan sebagai rakyat biasa? Rakyat yang unggul dalam hal jumlah ini, dapat menghimpun kekuatan dengan melakukan pengorganisasian diri, berjejaring dengan berbagai elemen gerakan sosial untuk memperkuat diri dalam menolak penindasan modal yang telah merampas hak dasar seluruh makhluk hidup untuk memperoleh pangan. Sementara itu negara harus menjamin kedaulatan pangan di tingkat keluarga di pedesaan, baik laki-laki, anak-anak, maupun perempuan, melalui penerapan sistem pertanian yang terpadu dan pengembangan beranekaragam tanaman pangan sehingga petani dan keluarganya dapat memperoleh makanan yang sehat secara berkelanjutan, memperkuat sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan yang berbasis pada sumber daya lokal, serta menyediakan ruang-ruang partisipasi bagi petani kecil untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pertanian (ink/2 Desember 2008/tulisan ini dimuat dalam Majalah SERASI (terbitan Kantor Menteri Lingkungan Hidup/2008).